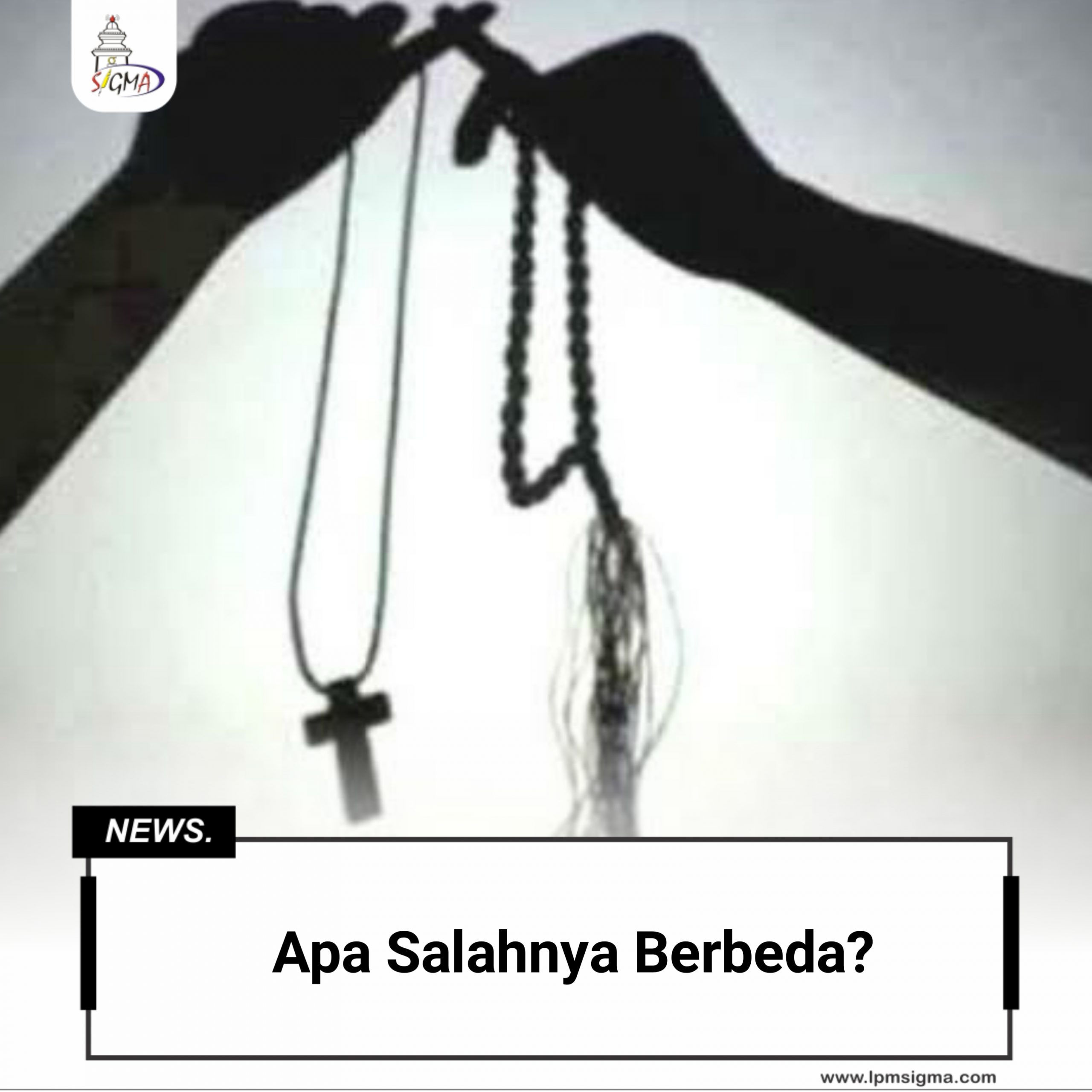Oleh: Nada Khovia
“Kok, di agama kamu salib di sembah-sembah?”
Itulah bentuk kalimat yang kerap dilontarkan kepada gadis berkulit hitam, Lia (bukan nama sebenarnya) adalah seorang siswi di salah satu SMA negeri di Pandeglang. Baginya menyesuaikan diri sebagai minoritas di sana sangat sulit. Tak jarang ia menerima pertanyaan atau omongan yang melukai hatinya.
“Seringkali menganggap agama lain itu salah serta menuduh saya dan agama saya adalah kafir,” ceritanya.
Bagi Lia pertanyaan yang kerap menyudutkan dirinya juga diterima dari teman-teman di sekolahnya. Ia sering menjadi pusat perhatian karena berbeda sendiri. Ia tidak mengenakan jilbab. Apalagi teman-teman sekolahnya saat itu belum mengenal agama yang dianutnya.
Berbaur dengan masyarakat yang memiliki rasa fanatik yang tinggi, tentu bukan hal yang mudah dalam melakukan berbagai aktivitas sosial. Bahkan berbagai bentuk diskriminasi sering kali ia dapatkan di lingkungan pendidikan.
“Ya, mereka anggap agama mereka yang benar. Saya sering disuruh masuk Islam,” kenang Lia.
Joseph (bukan nama sebenarnya) yang akrab dipanggil dengan nama Jo, juga mengalami hal yang tidak berbeda jauh dengan Lia. Sebagai minoritas dari kelompok masyarakat yang belum terbuka dengan perbedaan, Jo kerap menerima perlakuan berbeda karena agamanya berbeda dengan kebanyakan tetangganya.
Pernah suatu kali rumah Jo dilempari ampas tahu oleh masyarakat sekitar. Sering juga ia menerima lelucon terhadap agama dan Tuhan yang ia yakini. “Saya sedih, gak bisa lupa kejadian itu,” ujarnya.
Penolakan yang dialami oleh Lia dan Jo mungkin tak pernah dirasakan oleh Ustadz Ahmad (bukan nama sebenarnya). Terlahir sebagai mayoritas di tanah Pandeglang menjadikan dirinya sebagai orang yang menolak keberadaan agama lain selain agama yang diyakininya. Ia tak pernah membayangkan akan hidup bertetangga dengan orang berbeda agama.
“Saya menolak keras ada agama selain Islam masuk lingkungan ini. Apalagi ada gereja di Pandeglang, saya menolak,” tegasnya.
Selain hidup bertetangga ia juga menolak adanya bangunan rumah ibadah lain berdiri termasuk symbol apapun dari rumah ibadah agama lain. Hal ini dikarenakan ia tidak sepakat ada orang berbeda keyakinan.
“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka kita sama seperti kaum tersebut. Kalo kita mendukung masyarakat selain islam, ya sama aja kita memihak mereka. Gak akan ridho sampe kapanpun, kecuali mereka ikut kepada kita,” jelasnya kembali.
Sulitnya IMB untuk Rumah Ibadah
Pendeta Markus Taekz, Pendeta Gembala Sidang di Gereja Pantekosta Rahmat Carita Banten berangkat dari NTT ke Carita pada 1986. Mendirikan gereja dan hingga kini menetap di sana bersama istrinya, Rusman Anita Sitorus.
Gereja yang menjadi rumah ibadah bagi mereka berdua dan puluhan jemaat gereja lainnya masih terkendala izin mendirikan bangunan (IMB) hingga hari ini. Meskipun rumah ibadah itu sudah mendapatkan izin dari Binmas Kristen Kanwil Agama Jawa Barat. Menurut Pendeta Markus, pemerintah Kabupaten Pandeglang sebenarnya mengetahui keberadaan mereka, umat Kristiani. Hanya belum ada kebijakan resmi dari pemerintah terkait IMB rumah ibadah mereka.
“Pemerintah menerima keberadaan kami, hanya saja secara resmi tidak berani mengeluarkan izin atau melegalkan untuk pembangunan gereja karena berbagai tekanan,” paparnya.
Hingga kini Pendeta Markus dan pihak gereja Pantekosta Rahmat Carita terus melakukan mediasi dengan pemerintah untuk mendapatkan izin resmi. Mereka sudah pernah mengajukan perizinan sesuai prosedur namun belum membuahkan hasil.
Kini mereka terkendala Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua FKUB Pandeglang Entis Sutisna saat dikonfirmasi izin Gereja Pantekosta Rahmat Carita. Disampaikannya bahwa diperlukan 90 jemaat rumah ibadah dengan KTP setempat; dan persetujuan 60 orang warga sekitar rumah ibadah yang ditunjukkan dengan KTP untuk memproses pemberian izin rumah ibadah.
Namun kurangnya jumlah jemaat yang kebanyakan berasal dari luar wilayah rumah ibadah menjadi kendala. “Dalam pemenuhan jumlahnya tidak diperbolehkan mendatangkan jemaat dari luar desa, kecamatan, dan luar kabupaten,” tegasnya.
Entis sampaikan hingga kini FKUB Pandeglang belum pernah menerima usulan pendirian rumah ibadah selain Masjid.
Melihat sulitnya proses perizinan yang dialami, Pendeta Markus tetap berupaya agar izin diberikan. “Kalau sekarang kendalanya peraturanya 2 menteri itu, sementara kita ada sebelum peraturan itu ada, sejak 1986. Tapi kita akan coba melalui pengacara kita, yang penting kami sudah berusaha dan yang terpenting kami tetap bebas Ibadah aja,” sahutnya.
Pun hingga kini Pendeta Markus, ibu Anita dan jemaat gereja lainnya tetap berupaya agar dapat membaur dengan masyarakat sekitar. Membantu fasilitas penunjang masyarakat dengan pembuatan WC, berdonasi buku-buku untuk pesantren juga mereka lakukan.
“Itu cara kami menyesuaikan diri agar diterima oleh masyarakat, dengan membantu satu sama lain dan saling mendukung,” ujar Anita.
Disampaikan Entis bahwa hingga sekarang rumah ibadah non muslim yg ada data di FKUB ada 3 yakni; Labuan greja katolik, vihara budha 1 dan Carita 1 buah rumah ibadah sementara jemaat kristen protestan yg dipimpin pendeta Markus. Itu semua masih bersifat sementara, dan kalau ada rumah ibadah selain dari 3 (tiga) data di atas, seharusnya tidak boleh melakukan peribadatan.
Sementara itu, Deputy Director Human Rights Working Group (HRWG) Daniel Awigra tidak sepakat terhadap penyebutan pemberian izin rumah ibadah. Menurutnya hal itu malah memperumit masyarakat minoritas di suatu daerah. Karena artinya untuk menunjukkan ekspresi keagamaan dengan mendirikan rumah ibadah, suatu kelompok agama membutuhkan persetujuan dari kelompok masyarakat agama lain.
Bagi Awigra harusnya tugas Negara dalam melindungi dan memenuhi hak setiap warha Negara terutama hak untuk merasa aman saat beribadah. “Saat diserahkan kepada warga sekitar dan kemudian mempersulit agama lain, di sinilah tugasnya negara untuk memfasilitasi,” sambungnya.
Terlepas dari kondisi kehidupan bermasyarakat di Pandeglang, Jo tak banyak berharap. Ia hanya ingin agar masyarakat di Kota Pandeglang dapat lebih paham dan menghargai perbedaan agama. Juga agar lebih menghormati masyarakat lain untuk beribadah sekalipun berbeda agama.
Anita sendiri menekankan agar pemerintah lebih transparan terkait data umat agama Kristen di Pandeglang. Data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Pandeglang menyebutkan umat Kristen di Pandeglang hanya 53 orang, nyatanya ada lebih dari 2000 KK yang bermukim di sana. Data yang tidak sesuai dengan yang ada di lapangan akan menyebabkan misinformasi dan kesalahan persepsi. Seperti kebutuhan akan rumah ibadah yang memadai.
“Saya ingin Pandeglang lebih toleran dan terbuka untuk perubahan, terutama perkembangan masyarakat. Serta harus mau mengakui keberadaan umat agama lain yang ada di Pandeglang,” harapnya.
Tulisan ini bagian dari program Workshop Pers Mahasiswa yang digelar Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK) kerja sama dengan Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.